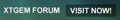Substansi Syariat Islam
Definisi Syariat Islam
Kata syariat Islam merupakan pengindonesiaan dari kata Arab, yakni as-syarî‘ah al-Islâmiyyah. Secara etimologis, kata as-syarî’ah mempunyai konotasi masyra‘ah al-mâ’ (sumber air minum).1 Orang Arab tidak menyebut sumber tersebut dengan sebutan syarî‘ah kecuali jika sumber tersebut airnya berlimpah dan tidak pernah kering.2 Dalam bahasa Arab, syara‘a berarti nahaja (menempuh), awdhaha (menjelaskan), dan bayyana al-masâlik (menunjukkan jalan). Syara‘a lahum-yasyra‘u-syar‘an berarti sanna (menetapkan).3 Syariat dapat juga berarti madzhab (mazhab) dan tharîqah mustaqîmah (jalan lurus).4
Dalam istilah syariat sendiri, syarî‘ah berarti agama yang ditetapkan oleh Allah SWT untuk hamba-hamba-Nya yang terdiri dari berbagai hukum dan ketentuan yang beragam.5 Hukum-hukum dan ketentuan tersebut disebut syariat karena memiliki konsistensi atau kesamaan dengan sumber air minum yang menjadi sumber kehidupan bagi makhluk hidup. Dengan demikian, syariat dan agama mempunyai konotasi yang sama,6 yaitu berbagai ketentuan dan hukum yang ditetapkan oleh Allah SWT bagi hamba-hamba-Nya.
Sementara itu, kata al-Islâm (Islam), secara etimologis mempunyai konotasi inqiyâd (tunduk) dan istislâm li Allâh (berserah diri kepada Allah). Istilah tersebut selanjutnya dikhususkan untuk menunjuk agama yang disyariatkan Allah SWT kepada Nabi Muhammad saw. Dalam konteks inilah, Allah menyatakan kata Islam sebagaimana termaktub dalam firman-Nya:
ِ﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي
وَرَضِيتُ لَكُمُ الإِْسْلاَمَ دِينًا﴾
Hari ini Aku telah menyempurnakan untuk kalian agama kalian, mencukupkan nikmat-Ku atas kalian, dan meridhai Islam sebagai agama bagi kalian. (QS al-Mâ’idah [5]: 3).
Karena itu, secara syar‘î, Islam adalah agama yang diturunkan oleh Allah SWT kepada junjungan kita, Muhammad saw., untuk mengatur hubungan manusia dengan Penciptanya, dirinya sendiri, dan sesamanya.7 Hubungan manusia dengan Penciptanya meliputi masalah akidah dan ibadah; hubungan manusia dengan dirinya sendiri meliputi akhlak, makanan, dan pakaian; hubungan manusia dengan sesamanya meliputi muamalat dan persanksian.8
Dengan demikian, syariat Islam merupakan ketentuan dan hukum yang ditetapkan oleh Allah atas hamba-hamba-Nya yang diturunkan melalui Rasul-Nya, Muhammad saw., untuk mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya, dengan dirinya sendiri, dan dengan sesamanya. Artinya, cakupan syariat Islam meliputi akidah dan syariat. Dengan kata lain, syariat Islam bukan hanya mengatur seluruh aktivitas fisik manusia (af‘âl al-jawârih), tetapi juga mengatur seluruh aktivitas hati manusia (af‘âl al-qalb) yang biasa disebut dengan akidah Islam. Karena itu, syariat Islam tidak dapat direpresentasikan oleh sebagian ketentuan Islam dalam masalah hudûd (seperti hukum rajam, hukum potong tangan, dan sebagainya); apalagi oleh keberadaan sejumlah lembaga ekonomi yang menjamur saat ini semisal bank syariah, asuransi syariah, reksadana syariah, dan sebagainya.
Ruang Lingkup Syariat Islam
Dengan definisi syariat Islam baik secara etimologis maupun terminologis syar‘î di atas, tampak jelas bahwa ruang lingkup syariat Islam adalah seluruh ajaran Islam, baik yang berkaitan dengan akidah maupun peraturan atau sistem kehidupan yang menjadi turunannya.
Akidah Islam adalah keimanan kepada Allah dan para malaikat-Nya; pada kitab-kitab-Nya; kepada para rasul-Nya; serta pada Hari Akhir dan takdir, yang baik dan buruknya berasal dari Allah SWT semata.9 Akidah Islam juga meliputi keimanan pada adanya surga, neraka, dan setan serta seluruh perkara yang berkaitan dengan semua itu. Demikian juga dengan hal-hal gaib dan apa saja yang tidak bisa dijangkau oleh indera yang berkaitan dengannya.10 Akidah Islam merupakan pemikiran yang sangat mendasar (fikr asâsi). Ia mampu memecahkan secara sahih problem mendasar manusia di seputar: dari mana manusia berasal; untuk apa manusia ada; dan mau ke mana manusia setelah mati.11 Artinya, akidah Islam merupakan pemikiran yang menyeluruh (fikrah kulliyyah) yang menjadi sumber dari seluruh pemikiran cabang. Ia adalah pemikiran mendasar yang membahas persoalan di seputar: (1) alam semesta, manusia, dan kehidupan; (2) eksistensi Pencipta dan Hari Akhir; (3) Hubungan alam, manusia, dan kehidupan dengan Pencipta dan Hari Akhir. Dalam konteks manusia, hubungan yang dimaksud adalah hubungan dirinya sebagai hamba dengan Allah yang harus tunduk pada syariat-Nya. Sebab, syariat Allah merupakan standar akuntalibitas bagi seluruh aktivitas manusia di hadapan-Nya.12
Sementara itu, peraturan atau sistem kehidupan Islam merupakan kumpulan ketentuan yang mengatur seluruh urusan manusia; baik yang berkaitan dengan ubudiah, akhlak, makanan, pakaian, muamalat, maupun persanksian.13 Tentu saja, untuk bisa disebut sistem Islam, ia harus digali dari dalil-dalil tafshîli (rinci); baik yang bersumber dari al-Quran, Hadis Nabi, Ijma Sahabat, maupun Qiyas.
Al-Quran, misalnya, dengan tegas menyatakan:
﴿وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ﴾
Kami telah menurunkan al-Kitab (al-Quran) ini kepadamu (Muhammad) untuk menjelaskan segala sesuatu. (QS an-Nahl [16]: 89).
Hadis Nabi juga telah menjelaskan hal yang sama:
»قَالَ تَرَكْتُ فِيكُمْ أَمْرَيْنِ لَنْ تَضِلُّوا مَا تَمَسَّكْتُمْ بِهِمَا كِتَابَ اللهِ وَسُنَّةَ نَبِيِّهِ «
Aku telah meninggalkan dua perkara yang menyebabkan kalian tidak akan sesat selamanya selama kalian berpegang teguh pada keduanya, yaitu Kitabullah dan Sunnah Nabi-Nya. (HR at-Turmudzî, Abû Dâwud, Ahmad).
Dari dua nash di atas, tampak jelas bahwa syariat Islam yang ditinggalkan oleh Rasulullah saw. telah mengatur segala urusan tanpa kecuali; mulai dari hubungan manusia dengan Penciptanya—dalam konteks akidah dan ibadah semisal shalat, puasa, zakat, haji dan jihad; hubungan manusia dengan dirinya sendiri seperti dalam urusan pakaian, makanan dan akhlak; hingga hubungan manusia dengan sesamanya seperti dalam urusan pemerintahan, ekonomi, sosial, pendidikan, dan politik luar negeri, dll. Secara konseptual, semuanya telah diatur oleh Islam dengan sejelas-jelasnya.
Sementara itu, dalam tataran praktis atau aplikatif, Islam juga memiliki tatacara tertentu yang digunakan untuk mengaplikasikan hukum-hukumnya, memelihara akidahnya, dan mengembannya sebagai risalah dakwah. Dengan demikian, yang pertama bersifat konseptual dan tidak mempunyai pengaruh secara fisik sehingga disebut sebagai fikrah (konsep) saja, sedangkan yang kedua bersifat praktis dan aplikatif sehingga disebut dengan tharîqah (metode). Sebab, yang terakhir ini tidak hanya bersifat konseptual, tetapi juga bersifat praktis dan aplikatif karena merupakan aktivitas fisik yang mempunyai pengaruh secara fisik, di samping bersifat tetap.
Kedua fakta di atas bisa dijelaskan lebih jauh. Akidah Islam, kewajiban shalat, zakat, haji, dan puasa, misalnya, adalah fikrah. Sementara itu, jihad, dakwah, dan sanksi atas tindakan kriminal (‘uqûbât) adalah tharîqah karena merupakan aktivitas fisik yang mempunyai pengaruh secara fisik dan bersifat tetap; tidak berubah karena situasi dan kondisi.14 Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa syariat Islam mencakup fikrah dan tharîqah.
Karena syariat Islam terdiri dari fikrah dan tharîqah, keduanya harus diyakini secara utuh; tidak boleh dipisahkan satu sama lain. Mengimani fikrah-nya saja (semisal kewajiban menegakkan shalat dan haramnya meninggalkan zakat) tanpa meyakini tharîqah untuk mengaplikasikannya semisal (keharusan memberlakukan sanksi ta’zîr bagi para pelanggarnya) bukan hanya akan mengakibatkan terabaikannya pelaksanaan syariat Islam tersebut, tetapi juga dapat mengantarkan siapa saja yang mengingkarinya pada kekufuran—jika yang diingkarinya adalah hukum-hukum yang bersifat tegas/pasti (qath‘î) dari segi sumber (tsubût) dan makna (dalâlah)-nya.
Dengan ungkapan lain, syariat Islam sesungguhnya meliputi keyakinan spiritual (‘aqîdah rûhiyyah) dan ideologi politik (‘aqîdah siyâsiyyah). Spiritualisme Islam telah membahas hubungan pribadi manusia dengan Tuhannya yang terangkum dalam akidah dan ubudiah; membahas pahala dan dosa manusia; serta membahas seluruh urusan keakhiratan manusia seperti surga dan neraka. Sebaliknya, ideologi politik Islam telah membahas seluruh urusan keduniaan yang terangkum dalam hubungan manusia dengan dirinya sendiri maupun dengan sesamanya; baik menyangkut bidang pemerintahan, ekonomi, sosial, pendidikan, maupun politik luar negeri, dan sebagainya.15 Istilah ‘aqîdah (keyakinan, prinsip dasar, ideologi) sengaja digunakan untuk menyebut kedua konsepsi di atas. Alasannya, karena masing-masing aspek tersebut merupakan ajaran Islam yang harus diyakini oleh setiap Muslim dan merupakan persoalan agama yang telah sama-sama diketahui urgensinya (ma‘lûm min ad-dîn bi adh-dharûrah). Penolakan terhadap salah satu atau kedua-duanya sekaligus dapat mengakibatkan seseorang terpelanting dari Islam alias murtad.
Dari sini, dapat disimpulkan, bahwa syariat Islam bukan hanya mengatur urusan dan persoalan yang dibahas oleh agama, tetapi juga urusan dan persoalan yang dibahas oleh ideologi. Dengan lingkup syariat Islam yang meliputi dua wilayah ini—agama dan ideologi—maka tepat sekali jika Islam disebut sebagai agama dan ideologi sekaligus. Artinya, secara mendasar, Islam jelas berbeda dengan Kristen, Yahudi, Hindu, Budha, dan sebagainya yang bersifat spiritual. Syariat agama-agama non-Islam di atas pada faktanya hanya membahas urusan dan persoalan spiritual (keakhiratan) sehingga hanya layak disebut sebagai agama. Sebaliknya, urusan dan persoalan keduniaan yang dibahas oleh ideologi, tidak dibahas oleh agama-agama non-Islam tersebut. Islam juga berbeda dengan ideologi-ideologi lain seperti Kapitalisme dan Sosialisme. Kedua ideologi tersebut pada faktanya juga hanya membahas urusan dan persoalan keduniaan semata. Sebaliknya, urusan dan persoalan spiritual (keakhiratan) yang dibahas oleh agama tidak dibahas oleh keduanya. Karena itu, baik Kapitalisme maupun Sosialisme tidak dapat disebut sebagai agama, tetapi lebih tepat disebut sebagai ideologi.
Walhasil, Islamlah—dengan syariatnya—satu-satunya yang ada di dunia ini yang membahas seluruh urusan dan persoalan keduniaan maupun keakhiratan dengan sempurna. Artinya, hanya Islamlah satu-satunya syariat di dunia ini yang utuh dan sempurna, yang dapat diimplementasikan sebagai agama dan ideologi sekaligus.
Keluasan dan Fleksibelitas Syariat Islam
Dari uraian di atas, dapat dibuktikan bahwa syariat Islam mempunyai lingkup yang sangat luas; mencakup seluruh urusan dan persoalan kehidupan manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Allah SWT berfirman:
﴿وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ﴾
Kami telah menurunkan al-Kitab (al-Quran) ini kepadamu (Muhammad) untuk menjelaskan segala sesuatu. (QS an-Nahl [16]: 89).
﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي
وَرَضِيتُ لَكُمُ الإِْسْلاَمَ دِينًا﴾
Hari ini Aku telah menyempurnakan untuk kalian agama kalian, telah mencukupkan nikmat-Ku untuk kalian, dan telah meridhai Islam sebagai agama kalian. (QS al-Mâ’idah [3]: 3).
Kedua ayat ini membuktikan cakupan Islam yang meliputi seluruh urusan manusia. Urusan-urusan tersebut semuanya telah dijelaskan oleh Islam. Syariat Islam yang mengatur seluruh urusan tersebut telah disempurnakan oleh Allah sehingga tidak ada sedikitpun kekurangan di dalamnya. Dengan kata lain, tidak ada satu pun persoalan dan urusan kehidupan manusia yang tidak dijelaskan oleh Islam.
Keluasan syariat Islam terlihat dari cakupannya yang meliputi seluruh urusan dan persoalan kehidupan manusia; mulai dari yang bersifat duniawi hingga yang bersifat ukhrawi; dari yang bersifat vertikal (hubungan manusia dengan Tuhannya), horisontal (hubungan manusia dengan sesamanya), hingga persoalan personal (hubungan manusia dengan dirinya sendiri). Semua itu terepleksikan dalam urusan akidah dan ubudiah; pemerintahan, ekonomi, sosial, pendidikan, politik luar negeri, dan sanksi hukum; akhlak, makanan, dan pakaian. Semuanya telah dibahas tuntas dan jelas oleh syariat Islam. Penggalian berbagai hukum terhadap nash-nash syariat, yakni al-Quran dan Sunnah Nabi, memungkinkan dipecahkannya berbagai kasus dan persoalan yang beragam. Kasus-kasus perburuhan, misalnya, baik negeri ataupun swasta, dapat diselesaikan dengan hukum syariat yang digali dari firman Allah berikut:
﴿فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ﴾
Jika mereka (para wanita itu) menyusui untuk (anak-anak) kalian, berikanlah upah-upah mereka. (QS at-Thalâq [65]: 6).
Secara eksplisit, ayat ini menjelaskan hak wanita yang dicerai atas upah menyusui yang dilakukannnya terhadap anak hasil pernikahan antara dirinya dan bekas suaminya. Dari kasus upah wanita yang dicerai ini lahir definisi syar‘î mengenai akad perburuhan (ijârah), yaitu akad atas jasa tertentu dengan kompensasi tertentu.16 Definisi ini merupakan bagian dari hukum syariat yang relevan untuk diimplementasi pada seluruh kasus perburuhan, baik buruh khusus maupun umum. Definisi ini juga dapat digunakan untuk menghukumi status akad kekhalifahan antara khalifah dan umat atau akad antara khalifah serta para pembantu dan walinya, yakni bahwa mereka tidak diangkat berdasarkan akad perburuhan (‘aqd al-ijârah). Artinya, mereka tidak layak mendapatkan upah sebagaimana halnya buruh, tetapi sekadar mendapatkan kompensasi atau santunan non-gaji.17 Karena bukan akad perburuhan, mereka juga tidak dapat diberhentikan oleh umat, karena umat bukan majikan mereka, dan mereka bukan buruh umat. Mereka hanya dapat diberhentikan oleh mahkamah mazhâlim (sejenis mahkamah agung, peny.) sebagai institusi yang berfungsi untuk menghilangkan kezaliman yang dilakukan oleh aparat pemerintahan.
Namun demikian, tidak semua nash-nash syariat yang bersumber dari al-Quran dan Sunnah Nabi membahas seluruh persoalan kehidupan manusia secara rinci/mendetail (mufashshal). Sebagian besar nash-nash tersebut bahkan hanya menjelaskan hukum-hukum tertentu secara global (mujmal) dengan makna-makna yang bersifat general (ma’ân ‘âmmah). Sementara itu, rinciannya diserahkan pada mekanisme ijtihad para mujtahid, yaitu ketika bentuk dan makna yang bersifat global dan general tersebut hendak diimplementasikan sesuai dengan kondisi kasus-perkasus pada setiap waktu dan tempat. Hukum waris, misalnya, di satu sisi dinyatakan secara rinci (mufashshal) di dalam al-Quran. Akan tetapi, dalam sebagian kasus tertentu, hukum waris memerlukan ijtihad seorang mujtahid, seperti dalam kasus kalâlah. Sebagaimana diketahui, Allah SWT berfirman:
﴿وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلاَلَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ
فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ﴾
Jika seseorang yang mati—baik laki-laki maupun perempuan—adalah kalâlah, sementara ia mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), maka bagi masing-masing saudaranya itu seperenam harta. (QS an-Nisâ’ [4]: 12).
Ketika Abû Bakar ditanya mengenai pengertian kalâlah, beliau menjawab, “Kalâlah adalah orang yang tidak memiliki bapak maupun anak.”18
Sebaliknya, ‘Umar bin al-Khaththâb berpendapat yang berbeda dengan Abû Bakar. Menurutnya, kalâlah adalah orang yang tidak mempunyai anak saja. Akan tetapi kemudian, sebelum meninggal, ‘Umar meninggalkan pendapatnya dan kembali merujuk pada pendapat Abû Bakar.19 Perbedaan antara Abû Bakar dan ‘Umar ini wajar terjadi karena nash yang menjelaskan kasus kalâlah ini tidak rinci (ghayr mufashshal).
Dengan adanya nash-nash syariat yang bersifat global (mujmal) dan general (‘âmmah), setiap dinamika, perubahan, dan perkembangan persoalan yang berlangsung di tengah manusia sangat mungkin direspon dan diselesaikan dengan cepat oleh para mujtahid. Sekalipun demikian, adanya perubahan dan perkembangan realitas yang terjadi tidak berarti nash-nash syariat tunduk pada realitas yang ada. Sebaliknya, realitas tersebutlah yang harus tunduk pada nash-nash syariat. Dalam hal ini, Islam telah mensyariatkan satu metode untuk menyelesaikan seluruh problem yang berkembang, yakni menyeru para mujtahid untuk mempelajari problem yang terjadi sampai benar-benar dipahami, memahami nash-nash syariat yang relevan dengan kasus yang terjadi, dan baru setelah itu menggali atau mengimplementasikan hukum atau pemecahan atas problem tersebut.20
Dengan cara seperti ini, keluasan nash-nash syariat untuk menghasilkan berbagai hukum syariat dan fleksibelitasnya sehingga dapat diimplementasikan dalam berbagai kasus telah menjadi ciri khas syariat Islam. Dengan karakter seperti inilah syariat Islam mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan seluruh problem dalam kehidupan manusia, baik di masa lalu, masa kini, maupun yang akan datang.
Di samping bukti-bukti normatif di atas, juga terdapat bukti-bukti historis, yakni perjalanan peradaban Islam yang sangat panjang dan sangat agung—selama hampir 13 abad—sebagai hasil dari diterapkannya syariat Islam di muka bumi. Bukti-bukti normatif maupun historis ini mengukuhkan bahwa selama metode penyelesaian berbagai persoalan yang terjadi—yang bersumber dari syariat Islam—diterapkan oleh umat Islam dan pintu ijtihad pun tetap dibuka, selama itu pula syariat tidak pernah kering akan solusi sekaligus tetap layak diterapkan di manapun dan kapanpun. Akan tetapi sebaliknya, ketika syariat Islam tidak diterapkan dan pintu ijtihad pun seolah telah ditutup, umat Islam menjadi mandul dan tidak mampu memecahkan berbagai persoalan yang terjadi. Inilah yang pernah dihadapi umat Islam pasca ‘ditutupnya’ pintu ijtihad oleh al-Qaffâl pada abad ke-4 Hijriah/10 Masehi dan pasca digusurnya syariat Islam seiring dengan diruntuhkannya Khilafah Islamiyah pada tahun 1924 oleh Kemal Attaturk yang berkonspirasi dengan Yahudi dan Inggris.
Hukum Tidak Berubah karena Faktor Waktu dan Tempat
Karakteristik hukum Islam sangat berbeda secara diametral dengan hukum produk Kapitalisme maupun Sosialisme. Hukum Islam dibangun berdasarkan nash-nash syariat yang tetap. Dalam Islam, nash-nash syariat adalah sumber hukum yang kemudian menghukumi realitas. Sebaliknya, dalam Kapitalisme, misalnya, realitaslah yang menjadi pijakan hukum yang kemudian menghasilkan produk-produk hukum yang sesuai dengan (mengakomodasi) realitas.21 Akibatnya, hukum produk Kapitalisme ini berubah-ubah dari waktu ke waktu dan berbeda-beda antara satu tempat dan tempat lainnya. Ini adalah konsekuensi dari dijadikannya realitas—yang terus berubah dan berkembang—sebagai pijakan hukum. UU Pemilu Tahun 1999, misalnya, yang notabene baru dan dianggap paling baik dibandingkan dengan UU Pemilu sebelumnya, kini telah direvisi dengan alasan mempunyai kelemahan-kelemahan seiring dengan tuntutan dan perkembangan baru jagat perpolitikan di Tanah Air. Sementara itu, hukum produk Sosialisme dibangun berdasarkan hipotesis-teoretis yang diasumsikan ada dalam permasalahan yang terjadi.22
Sebagaimana telah dijelaskan, produk hukum Islam digali dari nash-nash syariat, sementara pada saat yang sama nash-nash tersebut tidak tetap dan tidak pernah mengalami perubahan. Karena itu, produk hukum tersebut harus selalu terikat dengan nash dan tunduk pada apa yang dinyatakan oleh dalâlah-nya. Pertimbangan atas dasar ‘perubahan zaman’ dan perbedaan tempat tidak mempunyai nilai sama sekali di sini, sebagaimana pertimbangan atas dasar kemaslahatan atau kemadaratan.
Perbedaan kultur, kebiasaan, dan adat istiadat masyarakat juga tidak boleh mempengaruhi hukum Islam. Sebab, kultur, kebiasaan, dan adat-istiadat bukanlah ‘illat (motif diberlakukannya hukum) dan sumber hukum. Bahkan, kultur, kebiasaan, dan adat-istiadat acapkali banyak yang bertentangan dengan syariat. Apalagi kultur, kebiasaan, dan adat-istiadat yang ada pada masa sekarang ini pada dasarnya merupakan kristalisasi dari pemikiran dan hukum-hukum yang bersumber dari sistem sekular yang telah terbukti mengakibatkan kerusakan masyarakat. Namun demikian, jika kultur, kebiasaan, dan adat-istiadat tersebut tidak bertentangan dengan hukum Islam, ia dibolehkan (mubah). Hanya saja, kebolehannya bukan karena pertimbangan apa-apa kecuali karena memang dibolehkan oleh nash-nash syariat.
Sebagaimana dimaklumi, syariat Islam adalah yang itu-itu juga; tidak pernah berubah. Yang halal akan tetap halal dan yang haram akan tetap haram. Selamanya begitu hingga Hari Kiamat, karena wahyu Allah telah terputus dan syariat Islam telah sempurna. Karena itu, khamar, misalnya, tidak akan pernah haram pada satu waktu, kemudian berubah menjadi halal pada waktu lain. Demikian juga keharaman riba, memata-matai orang Islam, menipu, meminta bantuan kepada orang kafir, suap, dan sebagainya. Statemen bahwa hukum harus berubah karena faktor perubahan waktu dan tempat tentu merupakan bentuk keberanian yang luar biasa terhadap Allah. Allah SWT berfirman:
﴿وَلاَ تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلاَلٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللهِ الْكَذِبَ
لاَ يُفْلِحُونَ﴾
Janganlah kalian berdusta dengan sebab apa yang disifatkan oleh lidah kalian, “Ini halal dan ini haram,” untuk mengada-adakan sesuatu yang dusta terhadap Allah. Sesungguhnya orang-orang yang berdusta terhadap Allah tidak akan berhasil. (QS an-Nahl [16]: 116).
Apabila hukum Islam harus berubah karena faktor waktu dan tempat, berarti akan ada satu fakta atau kasus yang memiliki dua hukum sekaligus—halal dan haram—meskipun dalam wilayah dan rentang waktu yang tidak sama. Ini jelas mustahil karena Allah tidak mungkin menurunkan dua hukum yang berlawanan untuk kasus yang sama. Hal ini juga sangat kontradiktif dengan karakter kesempurnaan syariat Islam.
Memang, realitas yang menjadi obyek hukum boleh jadi mengalami perubahan, tetapi hukum atas realitas itu sendiri tentu saja tidak berubah. Dalam istilah para ahli fikih (fuqahâ’), obyek hukum biasa disebut manâth al-hukm.23 Dalam al-Quran dan as-Sunnah, misalnya, khamar sampai kapanpun dan di mana pun tetap diharamkan. Akan tetapi, ketika esensi khamar berubah menjadi cuka, maka ia menjadi halal. Dalam dua keadaan ini sebetulnya tidak dapat dikatakan telah terjadi perubahan hukum. Yang terjadi adalah perubahan manâth al-hukm yang memungkinkan dihasilkannya dua hukum yang berbeda: khamar tetap khamar dengan keharamannya; cuka tetaplah cuka dengan kehalalannya. Sebab, keduanya memiliki esensi dan manâth al-hukm yang berbeda.
Demikianlah, setiap hukum syariat mempunyai manâth al-hukm. Setiap terjadi perubahan manâth, pasti ada hukum lain untuk manâth yang baru tersebut. Manâth, menurut al-Ghazâli, tidak sama dengan ‘illat (latar belakang/motif diberlakukannya hukum).24 Sebab, tidak semua hukum mempunyai ‘illat, tetapi ia pasti mempunyai manâth. Karena itu, menurut as-Syâtibi, penentuan hukum atas manâth al-hukm harus tepat, dan hanya berlaku untuk manâth tersebut, tidak untuk yang lain.25
Contoh lain, orang sakit yang tidak mampu berdiri, boleh menunaikan shalat sambil duduk atau berbaring. Perubahan posisi dari sebelumnya wajib berdiri menjadi boleh duduk tidak dapat dikatakan sebagai perubahan hukum karena kondisi berbeda, tetapi karena memang adanya perbedaan hukum yang didasarkan pada dua manâth al-hukm yang memang berbeda: orang sehat tidak sama dengan orang sakit. Karena itu, orang sehat tetap wajib menunaikan shalat dengan berdiri, sedangkan orang sakit dibolehkan melaksanakan shalat sambil duduk atau berbaring. Jika hukum untuk orang sehat diberlakukan juga pada orang sakit, jelas keliru, karena masing-masing mempunyai manâth al-hukm yang berbeda. Demikian seterusnya.
Di samping itu, syariat Islam diberlakukan atas manusia dalam kapasitasnya sebagai manusia; bukan karena faktor suku, etnik, geografis, ataupun karena faktor Arab atau non-Arabnya. Di mana pun dan kapan pun, manusia, baik Arab atau non-Arab, esensinya sama; masing-masing mempunyai kebutuhan jasmaniah dan naluriah yang sama. Kondisi ini tidak pernah berubah. Karena itu, gagasan bahwa hukum harus berubah karena faktor waktu dan tempat sebenarnya bukan merupakan keniscayaan hidup manusia. Sebab, esensi kemanusiaan pada diri manusia tidak pernah mengalami perubahan. Yang berubah hanyalah sarana fisik dan wujud materi yang melingkupinya. Dengan demikian, dinamisasi, perkembangan, dan perubahan tersebut sebenarnya hanya menyangkut bentuk-bentuk materi atau sarana-sarana fisik yang dimanfaatkan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan jasmaniah dan naluriahnya. Sebaliknya, kebutuhan-kebutuhan manusia, baik untuk memenuhi tuntutan jasmaniah maupun naluriahnya, tidak pernah berubah. Contoh, manusia memerlukan makanan, minuman, pakaian, tidur, beristirahat. Semua ini diperlukan oleh manusia pada zaman mana pun dan di mana pun meskipun boleh jadi alat pemuas dan kualitasnya berbeda-beda. Alat pemuas dan kualitas kebutuhan manusia zaman purba, misalnya, tentu berbeda dengan alat pemuas dan kualitas yang dibutuhkan manusia pada zaman modern meskipun kebutuhan mereka untuk makan, minum, berpakaian, tidur, dan istirahat tidak pernah berubah.
Karena itulah, berkaitan dengan benda-benda sebagai alat pemuas kebutuhan manusia, Islam telah menggariskan kaidah hukum yang sama yang berlaku untuk segala tempat dan segala zaman, yakni:
[اَلأَصْلُ فِي اْلأَشْيِاءِ الإِبَاحَةُ مَالَمْ يَرِدْ دَلِيْلُ التَّحْرِيْمِ]
Hukum asal benda (barang) adalah mubah selama tidak ada dalil yang mengharamkannya. 26
Sebaliknya, berkaitan dengan perbuatan yang ditujukan untuk memenuhi berbagai kebutuhan jasmaniah maupun naluriah—yang tidak pernah berubah itu—Islam menggariskan kaidah berikut:
[اَلأَصْلُ فِي اْلأَفْعَالْ التَّقَيُدُ بِاْلأَحْكَامِ الشَّرْعِيَةِ]
Hukum asal perbuatan manusia adalah terikat dengan hukum syariat.27
Walhasil, propaganda atas gagasan bawha hukum harus berubah karena waktu dan tempat tidak mempunyai pijakan syariat yang jelas dalam Islam.
Syariat Islam dan Aspek Kemaslahatan
Pertimbangan kemaslahatan juga sering menjadi pijakan dalam menentukan hukum. Benarkah aspek kemaslahatan mempunyai tempat dalam penentuan hukum syariat ataukah sebaliknya, syariatlah yang menentukan ada dan tidaknya aspek kemaslahatan tersebut?
Kemaslahatan pada dasarnya adalah diperolehnya manfaat dan terhindarkannya kerusakan (jalb al-manâfi’ wa daf‘ al-mudhirrah). Menentukan suatu perkara itu maslahat atau tidak hanya otoritas syariat semata. Syariatlah yang dapat menentukan hakikat kemaslahatan tersebut. Sebab, kemaslahatan yang dimaksud tentu kemaslahatan bagi manusia dalam kapasitasnya sebagai manusia yang mempunyai kebutuhan jasmaniah dan naluriah. Memang, kemaslahatan adakalanya dapat ditentukan oleh akal maupun syariat. Masalahnya, mana kemaslahatan yang benar-benar sesuai dengan fitrah manusia: yang ditentukan oleh akal atau syariat?
Jika akal dibiarkan menentukan kemaslahatan sendiri, padahal sejatinya akal memiliki kemampuan yang terbatas, pasti ia tidak akan mampu menjangkau hakikatnya, karena akal juga tidak mungkin mampu memahami hakikat manusia. Yang dapat memahami hakikat manusia hanyalah Pencipta manusia, yakni al-Khâliq, Allah SWT.
Memang, manusia dapat saja menentukan suatu perkara itu maslahat atau tidak. Akan tetapi, dia tidak mungkin meenentukannya secara pasti. Padahal, menentukan kemaslahatan berdasarkan asumsi atau klaim hanya akan menyeret manusia ke dalam kehancuran. Sebab, adakalanya manusia mengira suatu perkara mengandung kemaslahatan, tetapi akhirnya terbukti menimbulkan kemadaratan. Demikian juga sebaliknya. Ini dari satu aspek. Sementara itu, dari aspek lainnya, dapat dikatakan bahwa penilaian akal atas aspek kemaslahatan tersebut dapat berubah dari waktu ke waktu dan berbeda antara satu tempat dan tempat lainnya. Artinya, kemaslahatan yang ditentukan oleh akal manusia pastilah bersifat asumtif sekaligus relatif.
Karena itu, akal tidak boleh dibiarkan untuk menentukan aspek kemaslahatan. Syariatlah—yang notabene bersumber dari Zat Yang Mahatahu—yang harus menentukannya. ٍSebab, hanya syariatlah yang mampu menentukan kemaslahatan dan kemadaratan yang hakiki. Karena itu, yang mesti dilakukan akal adalah sekadar mencerap suatu realitas sebagaimana apa adanya, lalu memahami nash syariat mengenai realitas tersebut, baru kemudian menerapkan nash tersebut atas pada realitas yang dimaksud. Jika relevan, di sana pasti ada kemaslahatan atau kemadaratan sebagaimana yang dinyatakan oleh syariat. Akan tetapi, jika tidak relevan, makna yang relevan dengan realitas tersebut harus dicari sehingga kemaslahatan atau kemadaratan yang dinyatakan oleh syariat tersebut dapat diketahui setelah hukum Allah atas realitas tersebut diketahui.
Walhasil, kemaslahatan yang hakiki pada dasarnya adalah kemaslahatan yang ditentukan oleh syariat, bukan yang ditentukan oleh akal yang serba relatif. Dalam hal ini, penting untuk dipahami, bahwa syariat pasti mengandung maslahat. Artinya, di mana ada syariat, di situ pasti ada maslahat. Demikianlah sebagaimana yang dinyatakan oleh kaidah ushul berikut:
[حَيْثُمَا كَانَ الشَّرْعُ فَثَمَّتِ اْلمَصْلَحَةُ]
Di mana pun ada syariat, di situ pasti ada maslahat. []
Catatan Kaki:
1 Ibn al-Manzhûr, Lisân al-’Arab, juz I, hlm. 175; al-Fayrûz al-Abâdi, al-Qâmûs al-Muhîth, juz I, hlm. 6672; Ar-Râzi, Mukhtâr as-Shahhâh, Maktabah Lubnân, Beirut, 1996, hlm. 294.
2 Ibn al-Manzhûr, ibid, hlm. 175; al-Fayrûz al-Abadi, ibid, hlm. 6672;
3 Ar-Râzi, op. cit., hlm. 294.
4 Al-Jurjâni, at-Ta’rîfât, Dâr al-Bayân li at-Turâts, t.t., hlm. 167; ‘Abd al-Karîm Zaydân, al-Madkhal li Dirâsah as-Syarî’ah al-Islâmiyyah, Muassasah ar-Risâlah, Beirut, cet. XIV, 1996, hlm. 34.
5 Al-Qurthûbi, al-Jâmi’ li Ahkâm al-Qur’ân., juz XVI, hlm. 163.
6 Ibn al-Manzhûr, op. cit., juz XI, hlm. 631.
7 An-Nabhâni, Nizhâm al-Islâm, Mansyûrât Hizb at-Tahrîr, Beirut, cet. VI, 2001, hlm. 69.
8 Ibid.
9 An-Nabhâni, Nizhâm al-Islâm, hlm. 73; An-Nabhâni, as-Syakhshiyyah al-Islâmiyyah, Dâr al-Ummah, Beirut, cet. V, 1997, juz I, hlm. 29.
9 An-Nabhâni, as-Syakhshiyyah, juz I, hlm. 191-192.
10 Muhammad Muhammad Ismâ’îl, al-Fikr al-Islâmi, Maktab al-Wa’y, Beirut, 1958, hlm. 9-10.
11 An-Nabhâni, Nizhâm, hal. 73; An-Nabhâni, as-Syakhshiyyah, juz I, hlm. 191.
12 An-Nabhâni, as-Syakhshiyyah, juz I, hlm. 192.
13 An-Nabhâni, Nizhâm, hlm. 74; An-Nabhâni, Mafâhîm Hizb at-Tahrîr, Mansyûrat Hizb at-Tahrîr, cet. VI, 2001, hlm. 36.
14 An-Nabhâni, Nizhâm, hlm. 24; An-Nabhâni, Mafâhîm Hizb, hlm. 55-58.
15 Hadits ash-Shiyâm, t.p., t.t.
16 An-Nabhâni, as-Syakhshiyyah, juz II, hlm. 327, hlm. 44; al-Muzni, Mukhtashar, Dâr al-Kutub al-Ilmiyyah, Beirut, 1998, hlm. 171; al-Jurjâni, at-Ta’rîfât, hlm. 23.
17 An-Nabhâni, Mafâhîm Hizb, hlm. 44.
18 Lihat: al-Qurthûbi, al-Jâmi’ li Ahkâm al-Qur’ân, Dâr as-Sya’b, Kaero, cet. II, 1373, juz V, hlm. 76.
19 Lihat: ‘Abd ar-Razzâq, Mushannaf, al-Maktab al-Islâmi, Beirut, cet. II, 1403, juz X, hlm. 304.
20 An-Nabhâni, Nizhâm, hlm. 74; Muhammad Husayn ‘Abdullâh, al-Wâdhih fi Ushûl al-Fiqh, Dâr al-Bayâriq, Beirut, cet. II, 1995. hlm. 369.
21 An-Nabhâni, an-Nizhâm al-Iqtishâdi fî al-Islâm, Dâr al-Ummah, Beirut, cet. IV, 1990, hlm. 55-56.
22 Ibid, hlm. 56.
23 Lihat: Rawwâs Qal’ah Ji, Mu’jam Lughât al-Fuqahâ’, Dâr an-Nafâ’is, Beirut, cet. I, 1996, hlm. 431; al-Ghazâli, al-Mustashfâ fi ‘ilm al-Ushûl, Dâr al-Kutub al-Ilmiyyah, Beirut, cet. I, 2000, hlm. 319; as-Syâtibi, al-Muwâfaqât, ed. Abdullâh Darâz, Dâr al-Kutub al-Ilmiyyah, Beirut, t.t., juz IV, hlm. 65.
24 Al-Ghazâli, al-Mustashfâ, hlm. 304.
25 As-Syâtibi, al-Muwâfaqât, juz III, hlm. 62.
24 Muhammad Ismâ’îl, al-Fikr, hlm. 35-37; as-Suyûthi, al-Asybâh wa an-Nadhâ’ir, Dâr al-Kutub al-Ilmiyyah, Beirut, t.t., hlm. 60.
25 Muhammad Ismâ’îl, ibid, hlm. 32-35; Athâ’ bin Khalîl, Taysîr al-Wushûl ilâ al-Ushûl, Dâr al-Ummah, Beirut, cet. IV, 2000, hlm. 13-15.